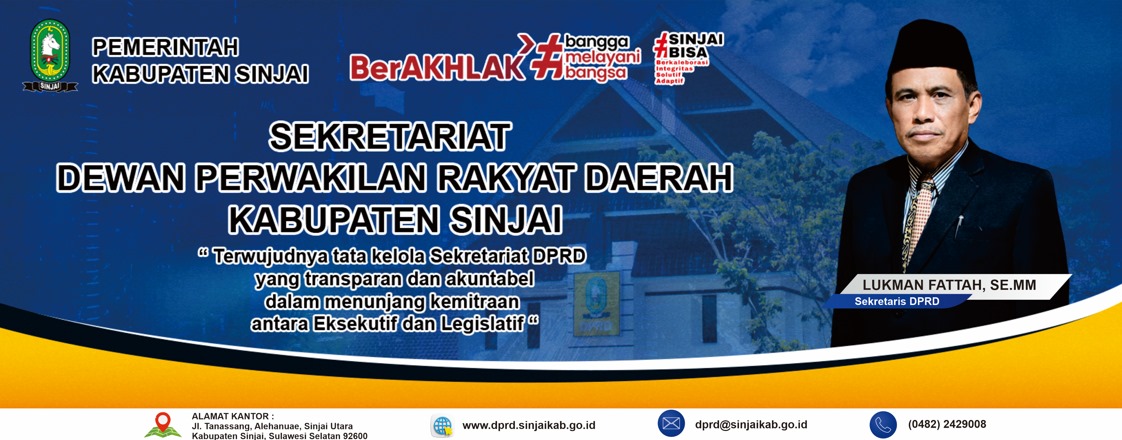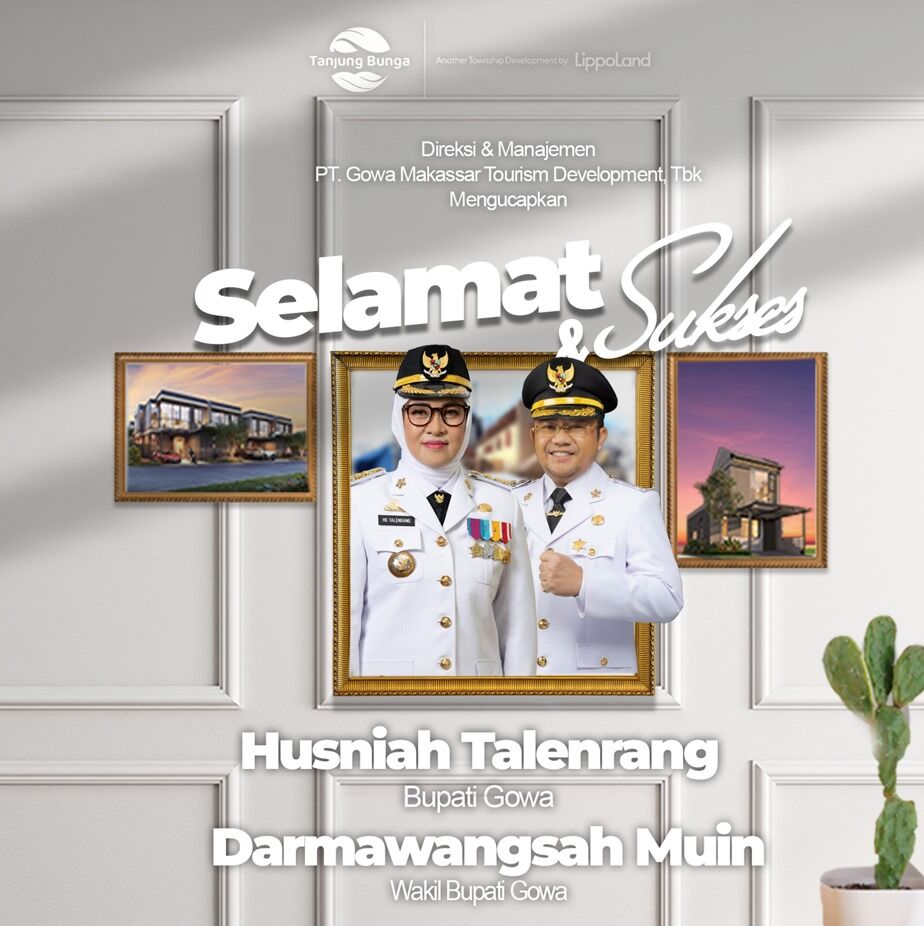Oleh: Arifai Ilyas
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen FEB Unhas
DI TENGAH dinamika pembangunan nasional, desa kini tidak lagi dipandang sebagai entitas pasif yang hanya menunggu program-program dari pemerintah pusat. Sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, arah pembangunan berubah secara signifikan: dari
pendekatan top-down menuju pemberdayaan desa berbasis potensi lokal. Salah satu instrumen paling strategis dalam agenda pembangunan desa tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BUMDes hadir sebagai lokomotif pembangunan desa. Ia bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan desa dalam mengelola sumber dayanya secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, tantangan masih membentang lebar. Oleh karena itu, perlu komitmen kolektif, penguatan kelembagaan, serta paradigma baru dalam tata kelola BUMDes agar benar-benar dapat menjalankan peran sentralnya sebagai motor penggerak pembangunan desa.
Paradigma Baru: Desa Sebagai Subjek Pembangunan
Sebelum hadirnya UU Desa, peran desa dalam pembangunan sangat terbatas. Desa lebih banyak menjadi objek program pembangunan, bukan subjek yang menentukan masa depannya sendiri. UU Desa membuka ruang bagi desa untuk merancang pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal. BUMDes menjadi instrumen konkret yang bisa mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
BUMDes bukan sekadar unit usaha. Ia adalah entitas legal yang memiliki otonomi untuk menjalankan bisnis dan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis desanya. Dengan demikian, BUMDes seharusnya menjadi jembatan antara potensi lokal dan pasar global.
Fungsi Strategis BUMDes dalam Pembangunan Desa
Fungsi strategis BUMDes terletak pada kemampuannya mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa secara kolektif. Tidak sedikit desa di Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, hasil pertanian unggulan, keindahan wisata, ataupun kerajinan tangan berkualitas tinggi. Masalahnya adalah keterbatasan akses terhadap pasar, modal, teknologi, dan manajemen usaha.
BUMDes dapat menjawab tantangan tersebut. Ia bisa menjadi agregator produk lokal, fasilitator promosi, hingga inkubator usaha mikro di desa. Melalui peran ini, BUMDes turut memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antara desa dan kota.
Dukungan Regulasi yang Kuat
Salah satu kekuatan utama BUMDes adalah basis hukumnya. Selain diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, BUMDes juga mendapatkan penguatan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Perubahan ini menempatkan BUMDes sebagai badan hukum yang dapat menjalin kerja sama bisnis, menerima penyertaan modal, serta mengembangkan unit usaha di berbagai sektor, dari jasa keuangan, pariwisata, pertanian, hingga layanan publik.
Regulasi ini juga mempertegas bahwa BUMDes bukanlah lembaga pemerintah, tetapi entitas ekonomi milik bersama yang dikelola secara profesional. Desa sebagai pemilik, bertindak melalui musyawarah desa untuk menentukan arah usaha dan evaluasi kinerja.
Tantangan Nyata di Lapangan
Namun, perjalanan BUMDes tidak selalu mulus. Banyak tantangan struktural dan kultural yang dihadapi. Pertama, banyak BUMDes belum berbadan hukum. Data menunjukkan bahwa lebih dari 19% BUMDes di Indonesia masih belum mengurus legalitasnya. Tanpa badan hukum, BUMDes kesulitan mengakses permodalan, menjalin kerja sama bisnis, maupun mengelola risiko secara sah.(Yuli Andri:2025).
Kedua, kualitas tata kelola BUMDes masih rendah. Laporan keuangan yang tidak tersusun, pelaporan usaha yang tidak transparan, hingga perencanaan usaha yang minim menjadi masalah umum.
Ketiga, minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital juga membatasi daya saing BUMDes di tengah era transformasi digital.
Keempat, tantangan sumber daya manusia. Tidak semua pengurus BUMDes memiliki kapasitas manajerial dan bisnis yang memadai. Sering kali, pengurus diangkat bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan sosial-politik dengan kepala desa.
Kelima, belum terbangunnya ekosistem kolaboratif antara BUMDes dengan pelaku usaha lokal, koperasi, BUMN, maupun institusi pendidikan. Padahal, penguatan BUMDes membutuhkan dukungan lintas sektor.
BUMDes Sebagai Agen Inovasi dan Digitalisasi Desa
Di tengah tantangan tersebut, muncul banyak BUMDes inspiratif yang mampu menjawab tantangan dengan inovasi. Sebut saja BUMDes Sekapuk di Gresik yang sukses mengelola wisata edukasi Setigi dan meraih keuntungan hingga miliaran rupiah per tahun. Atau BUMDes Sumber Sejahtera di Pujon Kidul yang berhasil mengembangkan kafe sawah sebagai destinasi wisata unggulan, sekaligus menyerap ratusan tenaga kerja lokal.(Yuli Adri:2025).
Kunci kesuksesan mereka adalah pengelolaan profesional, keterbukaan informasi, dan orientasi jangka panjang. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi menciptakan pengalaman dan nilai tambah. Di sinilah BUMDes bisa menjadi motor inovasi desa, mulai dari digitalisasi pemasaran, branding produk lokal, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pertanian dan produksi UMKM.
Program “One Village One Product”, “One Village One Innovation”, bahkan “One Village One Exporter” sangat relevan untuk didorong agar BUMDes menjadi pemain aktif dalam rantai nilai ekonomi lokal maupun nasional.
Strategi Memperkuat Peran BUMDes
Agar BUMDes benar-benar mampu menjadi lokomotif pembangunan desa, ada beberapa strategi yang perlu diperkuat:
1. Legalitas dan Tata Kelola
o Mendorong seluruh BUMDes segera berbadan hukum.
o Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang transparan dan partisipatif.
o Melakukan pelatihan manajemen bisnis dan akuntansi kepada pengurus.
2. Pemanfaatan Teknologi Digital
o Membangun platform e-commerce lokal desa.
o Melakukan digitalisasi sistem pencatatan keuangan dan inventaris aset.
o Mengembangkan kanal promosi digital (media sosial, marketplace, website).
3. Kemitraan Strategis
o BUMDes perlu menjalin kerja sama dengan koperasi, BUMN, BUMD, pelaku usaha swasta, lembaga pendidikan, dan sektor keuangan.
o Pemerintah daerah dan pusat juga perlu menyediakan inkubasi bisnis dan pendampingan intensif berbasis kebutuhan spesifik tiap desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
o Mendorong partisipasi warga dalam unit usaha BUMDes.
o Mengembangkan skema pembagian hasil usaha yang adil dan berkelanjutan.
o Menjadikan BUMDes sebagai alat pemerataan kesejahteraan desa, bukan hanya alat pencetak laba.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala
o Pemerintah desa wajib menggelar Musyawarah Desa secara berkala untuk mengevaluasi kinerja BUMDes.
o Laporan keuangan dan dampak sosial BUMDes harus terbuka dan dapat diakses publik.
Harapan: BUMDes adalah Masa Depan Desa
Jika dikelola dengan baik, BUMDes bukan sekadar badan usaha, tetapi akan menjelma sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang mampu mengangkat martabat desa. Ia menjadi alat distribusi kesejahteraan, tempat belajar kewirausahaan kolektif, dan titik temu antara tradisi lokal dengan inovasi modern.
BUMDes adalah wajah baru desa Indonesia yang mandiri dan kreatif. Namun, untuk sampai pada titik itu, kita butuh kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan tentu saja masyarakat desa itu sendiri. Penguatan regulasi tanpa implementasi adalah sia-sia. Dana desa tanpa inovasi hanya akan menghasilkan ketergantungan baru.
Sudah saatnya desa menjadi pilar utama pembangunan nasional. Dan di tengah arus pembangunan
itu, BUMDes harus tampil sebagai lokomotif—bukan gerbong yang hanya ikut tertarik. Sebab, dari desa yang kuat, Indonesia yang adil dan makmur bisa terwujud. (*)