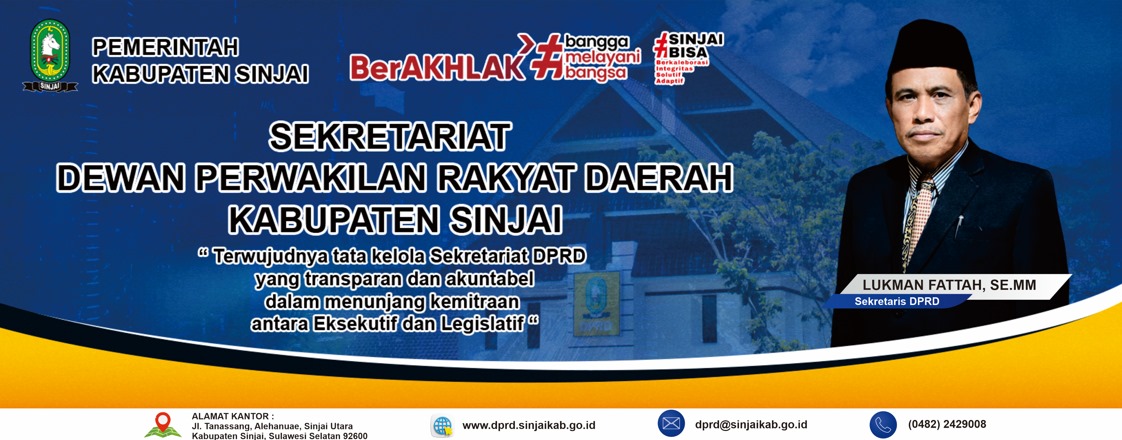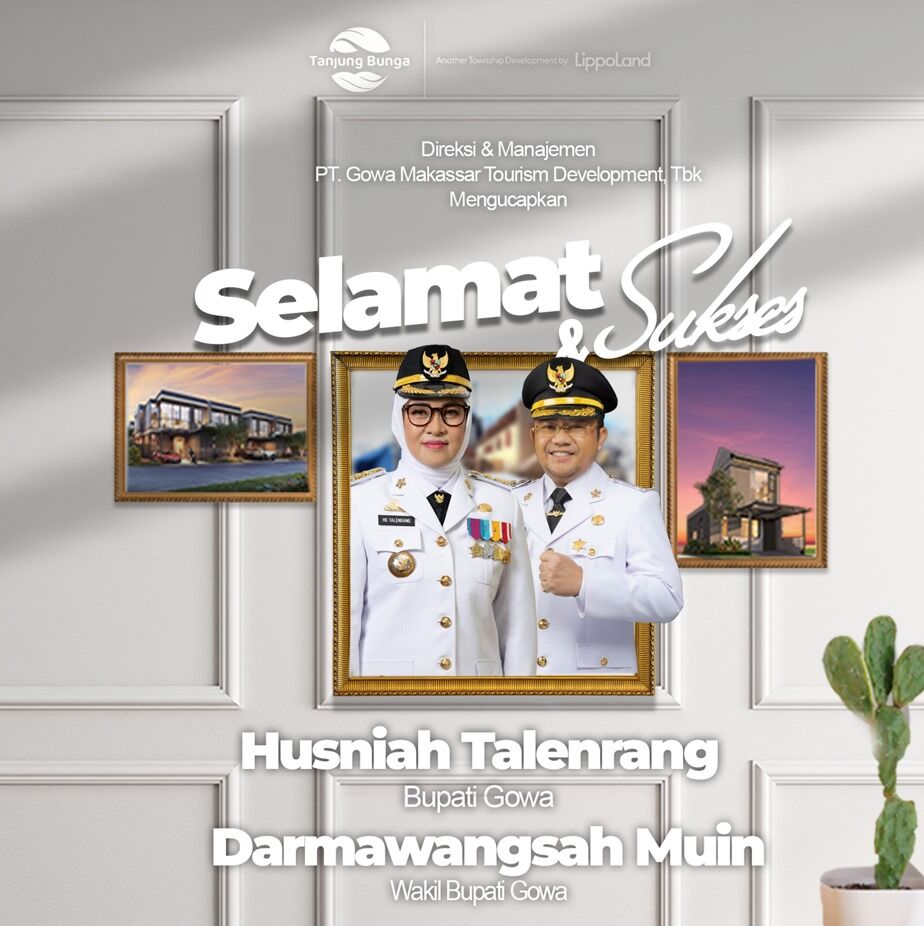Oleh: Arifai Ilyas
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen FEB Unhas
DALAM beberapa tahun terakhir, dunia mengalami guncangan demi guncangan yang menciptakan lanskap baru yang penuh ketidakpastian. Pandemi global, krisis ekonomi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi menjadi realitas yang tidak bisa dihindari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah segala kekacauan ini, satu hal yang semakin terbukti penting adalah mental resilience ketangguhan mental individu dan kolektif dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, sulit diprediksi, dan penuh tekanan.
Mental resilience bukan sekadar kemampuan untuk “kuat” menghadapi tekanan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan tumbuh melalui krisis. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ketangguhan mental bukan hanya dituntut dari individu semata, melainkan juga dari institusi, birokrasi, sistem politik, ekonomi, dan struktur sosial-budaya.
Tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana pentingnya membangun mental resilience di era ketidakpastian dengan menyoroti lima dimensi utama: birokrasi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Birokrasi: Reformasi yang Membumi dan Adaptif
Birokrasi adalah jantung penggerak roda pemerintahan. Namun, birokrasi yang lamban, kaku, dan terlalu prosedural sering kali menjadi hambatan utama dalam merespons dinamika yang cepat berubah. Di era ketidakpastian, birokrasi dituntut tidak hanya efisien, tapi juga resilien.
Mental resilience dalam birokrasi tercermin dalam kemampuan aparatur negara untuk bekerja di bawah tekanan, mengelola konflik, dan tetap produktif meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan tekanan politik. Salah satu contoh konkret adalah bagaimana pemerintah daerah
harus mampu menanggapi bencana alam atau krisis kesehatan tanpa menunggu terlalu banyak instruksi dari pusat.
Transformasi digital dalam pelayanan publik, peningkatan kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara), dan penguatan sistem meritokrasi menjadi bagian penting dari pembentukan resilience birokrasi. Tanpa ini, negara akan terus tertatih-tatih dalam menghadapi krisis, karena lengan eksekutifnya tidak cukup tangguh dan adaptif.
Politik: Stabilitas di Tengah Fragmentasi
Mental resilience dalam dunia politik berarti kemampuan elite dan sistem untuk menjaga stabilitas meski dalam tekanan, serta menciptakan ruang dialog di atas perbedaan. Politik yang resilient tidak alergi terhadap kritik, tidak rapuh oleh dinamika sosial, dan tidak reaktif terhadap tekanan luar. Ia justru mengambil peran sebagai penyaring konflik dan kanal aspirasi publik.
Ketahanan politik juga diuji dalam bagaimana partai politik, parlemen, dan lembaga eksekutif mampu membuat keputusan yang visioner dan berjangka panjang, bukan hanya populis dan jangka pendek.
Di era digital, ketika informasi berseliweran tanpa filter, narasi kebencian dan disinformasi dengan mudah memecah belah masyarakat. Politik yang sehat harus mampu menjadi jangkar bagi kestabilan sosial, bukan malah menjadi penyebab kegaduhan.
Sosial: Kohesi Komunal di Tengah Disrupsi
Resiliensi sosial merupakan salah satu fondasi paling vital dalam menghadapi krisis. Ketika struktur sosial longgar, masyarakat mudah terpecah, dan rasa saling percaya menurun, maka segala bentuk bantuan atau kebijakan akan menghadapi tembok resistensi.
Di era ketidakpastian, kita menyaksikan bagaimana komunitas-komunitas yang memiliki ikatan sosial kuat lebih mampu bertahan dari guncangan. Solidaritas warga saat pandemi COVID-19, misalnya, menunjukkan bahwa di luar struktur formal, masyarakat kita masih memiliki daya ikat yang luar biasa.
Namun, kita juga menyaksikan meningkatnya konflik horizontal, intoleransi, dan maraknya ujaran kebencian—yang semuanya menjadi ancaman terhadap resilience sosial.
Membangun ketahanan sosial berarti menguatkan jaringan sosial, memperkuat institusi sosial seperti keluarga dan organisasi kemasyarakatan, serta menciptakan ruang-ruang aman untuk dialog. Pendidikan karakter, inklusivitas, dan pemberdayaan kelompok marginal menjadi bagian penting dari strategi ini.
Ekonomi: Diversifikasi dan Kemandirian
Tidak ada ketahanan tanpa fondasi ekonomi yang kokoh. Ketahanan ekonomi bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan angka makroekonomi, tetapi juga mencakup ketangguhan struktur ekonomi terhadap guncangan eksternal: fluktuasi harga komoditas, gejolak pasar global, hingga disrupsi teknologi.
Indonesia terlalu lama bergantung pada sektor-sektor tertentu seperti ekspor komoditas mentah dan ekonomi informal. Saat pandemi melanda, jutaan orang kehilangan pekerjaan karena sektor informal sangat rentan terhadap gangguan. Inilah bukti bahwa kita membutuhkan diversifikasi ekonomi dan kebijakan yang mendorong kemandirian produksi, terutama pangan dan energi.
Mental resilience dalam ekonomi juga dituntut dari para pelaku usaha. UKM, sebagai tulang punggung ekonomi nasional, harus diperkuat bukan hanya dengan akses permodalan, tetapi juga pelatihan, digitalisasi, dan jejaring pasar. Ekonomi yang resilient adalah ekonomi yang tidak hanya besar, tetapi juga inklusif dan adaptif.
Budaya: Identitas Sebagai Sumber Ketangguhan
Sering kali kita lupa bahwa budaya adalah fondasi tak kasat mata yang sangat menentukan bagaimana masyarakat menghadapi krisis. Budaya tidak hanya soal tradisi atau kesenian, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kolektif, cara berpikir, dan kebiasaan dalam merespons situasi.
Mental resilience dalam budaya terlihat dari bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong, tepo seliro (tenggang rasa), dan musyawarah masih hidup dan memberi kekuatan dalam situasi sulit. Budaya lokal kita sebenarnya menyimpan banyak kearifan dalam membangun daya tahan baik terhadap bencana, kemiskinan, maupun konflik.
Namun, tantangan datang dari arus globalisasi dan modernisasi yang kadang menggusur nilai-nilai tersebut. Kita menghadapi krisis identitas, terutama di kalangan generasi muda, yang seringkali terputus dari akar budaya lokal.
Dalam jangka panjang, kehilangan identitas budaya akan membuat masyarakat rapuh terhadap tekanan luar dan mudah terombang-ambing oleh perubahan.Karena itu, pendidikan kebudayaan, pelestarian nilai lokal, dan inovasi berbasis budaya menjadi bagian dari strategi membangun resilience. Budaya yang hidup dan dinamis akan selalu mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri.
Harapan: Menjahit Kembali Ketahanan Kolektif
Mental resilience di era ketidakpastian bukan sekadar retorika motivasional atau wacana individualistik. Ia adalah sebuah proyek kolektif yang mencakup banyak dimensi kehidupan.
Birokrasi yang efisien, politik yang stabil, masyarakat yang kohesif, ekonomi yang inklusif, dan budaya yang kuat adalah simpul-simpul penting yang harus dikuatkan secara bersamaan.
Negara, masyarakat, dan individu harus menjahit kembali benang-benang ketahanan yang mungkin sudah rapuh, bahkan putus. Kita tidak bisa hanya berharap krisis berlalu; kita harus bersiap menghadapi krisis berikutnya dengan ketangguhan yang lebih tinggi.
Akhirnya, mental resilience bukan hanya soal bertahan, tapi soal bertumbuh. Di tengah dunia yang terus berubah, mereka yang tangguh bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi dan berevolusi dengan nilai dan tujuan yang tetap terjaga. Dan di situlah letak harapan kita bersama.